Habis Mukhlis Terbitlah Santoso
Hari-Hari ini Pada Tahun 1991 (2)
Aksi menginap gratis di emper ruang perawatan Mas Mukhlis di
Rumah Sakit Islam Siti Khodijah, Wonokromo, Surabaya, hari pertama berlangsung
lancar. Walau tidak bisa tidur nyenyak, tetap masih lebih enak. Setidaknya
tidak menguras isi dompet yang tak seberapa itu.
Sekitar pukul 05.00 saya berangkat ke kantor Jawa Pos di
Jalan Karah Agung, Ketintang Barat, untuk ikut tes. Saya sengaja berangkat
pagi-pagi agar tidak kesiangan tiba di lokasi. Maklum, butuh waktu dua jam
untuk berjalan kaki santai dari rumah sakit sampai di kantor Jawa Pos.
Sekitar pukul 07.00, saya sudah tiba di kantor Jawa Pos.
Suasana kantor masih sepi. Pelamar calon wartawan sepertinya belum berdatangan.
Atau memang yang diundang hanya sedikit.
Sambil menunggu jadwal tes yang masih dua jam lagi, saya
nongkrong di warung makan yang mangkal tak jauh dari kantor Jawa Pos. Waktu dua
jam cukup untuk sarapan dan baca-baca koran pagi.
Merasa tak tenang di warung, saya bergegas masuk ke kantor
Jawa Pos ketika jarum jam menunjuk ke angka 8. Ternyata di dalam sudah banyak
orang. Menurut informasi penitia seleksi, yang melamar ada 900 orang. Yang
dipanggil hanya 125 orang saja.
Saat tes dimulai, lima orang pelamar dipanggil ditemui lima
wartawan senior Jawa Pos. Saya menemui Pak Ali Murtadlo, redaktur halaman kota
Surabaya. Pak Ali membuka salam lalu mewawancarai saya dengan bahasa Inggris.
Matilah awak. Masalah terbesar saya muncul di awal seleksi!
Ah. Masa bodoh. Langsung saya sampaikan ke Pak Ali bahwa saya
tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Pak Ali hanya tertawa. ‘’Mas Joko,
Jawa Pos membutuhkan 11 wartawan. Yang 7 harus berbahasa Inggris baik. Yang 4
tidak perlu berbahasa Inggris baik,’’ kaya Pak Ali.
‘’Saya akan berusaha
masuk ke 4 yang tidak berbahasa Inggris baik saja,’’ jawab saya.
‘’Boleh. Tapi harus punya keunggulan, misalnya mampu menulis
berita lebih baik dari yang lain dan punya wawasan yang baik tentang hukum dan
kriminalitas,’’ kata Pak Ali.
‘’Wah, itu cocok dengan karakter saya Pak,’’ jawab saya.
‘’Anda senang dengan berita hukum dan kriminalitas?’’ tanya
Pak Ali.
‘’Kebetulan saya kuliah di fakultas hukum jurusan pidana dan
saya menulis skripsi tentang kriminalisasi hukum lingkungan,’’ jawab saya.
‘’Anda bisa memberikan contoh tulisan?’’ tanya Pak Ali.
‘’Saya punya banyak artikel yang sudah dimuat di surat kabar
di Semarang. Ada juga yang dimuat di Jawa Pos. Tapi sekarang tidak saya bawa.
Semua ada di berkas lamaran,’’ jawab saya.
‘’Anda kok bawa tas sampai dua? Apa isinya?’’ tanya Pak Ali.
‘’Yang ini mesin ketik Pak. Yang satunya baju ganti,’’ jawab
saya.
‘’Buat apa bawa mesin ketik?’’ tanya Pak Ali.
‘’Untuk menulis berita Pak. Siapa tahu hari ini ada tes
penulisan,’’ jawab saya.
Pak Ali tiba-tiba tertawa ngakak mendengar jawaban saya. ‘’Mas
Joko, Jawa Pos itu tidak menggunakan mesin ketik lagi. Di sini semua serba
komputer,’’ komentar Pak Ali.
‘’Saya juga bisa menulis dengan komputer Pak. Saya bisa menulis
dengan program Wordstar123 dan berhitung dengan program Lotus123,’’ jawab saya.
Setelah berdialog beberapa menit, Pak Ali memberikan selembar
kertas berisi daftar pertanyaan yang harus saya jawab. Ada pertanyaan tentang
kota Surabaya, peristiwa aktual yang terjadi di Surabaya, politik nasional dan
peristiwa internasional.
Usai menjalani tes, saya diperbolehkan pulang. ‘’Anda
menginap di mana?’’ tanya Pak Ali.
‘’Saya ada penginapan di Wonokromo Pak,’’ jawab saya.
‘’Penginapan apa di Wonokromo? Bukannya itu pasar dan
terminal?’’ tanya Pak Ali.
‘’Ada Pak. Penginapan Siti Khodijah. Penginapan kecil Pak. Tidak
terkenal,’’ jawab saya sambil malu-malu.
‘’Dekat dengan rumah sakit islam di situ ya,’’ tanya Pak Ali.
‘’Ya nempel di situ Pak,’’ jawab Pak Ali.
Saya lihat Pak Ali mengernyitkan keningnya. Saya menduga, dia
bingung dengan deskripsi lokasi penginapan saya, karena penginapan itu memang
tidak ada.
‘’Jangan lupa baca koran Jawa Pos besok pagi. Kalau nama Anda
tertera di situ, pukul 09.00 saya tunggu di kantor Jawa Pos. Ketemu saya lagi
ya,’’ pesan Pak Ali.
Dari Jawa Pos saya kembali ke RSI Siti Khodijah dengan
berjalan kaki. Beberapa kawan sesama pelamar yang sempat berkenalan menawarkan
jasa. Tapi saya memilih tidak menerima. Takut ketahuan kalau menginapnya di
rumah sakit.
Malam kedua menginap tidak adalah masalah. Demikian pula
malam ketiga. Semua lancar-lancar saja.
Problem muncul pada malam keempat. Sebab, Mas Mukhlis hari
itu ternyata sudah pulang. Berarti tidak ada alasan buat saya menginap di emper
kamarnya.
Terpaksa mengulang skenario dari awal. Secara kebetulan
selama tiga malam di rumah sakit, saya berkenalan dengan beberapa orang sesama
penunggu pasien.
Ada satu orang yang baru berkenalan pada malam ketiga.
Namanya Santoso. Dia menunggu istrinya yang sedang persiapan melahirkan anak
kedua.
Segera saya cari Mas Santoso di saal bersalin. Kebetulan dia
ada di sana. ‘’Sudah lahiran?’’ tanya saya.
‘’Belum. Mungkin masih dua atau tiga hari lagi,’’ jawab Mas
Santoso.
‘’Nunggu sama siapa mas malam ini?’’ tanya saya.
‘’Sendiri saja,’’ jawab Mas Santoso.
‘’Tenang mas, nanti malam saya temani,’’ kata saya.
‘’Wah terima kasih. Nanti malam boleh sambil main gaple,’’
jawab Mas Santoso.
Pucuk dicinta ulam tiba. Saat cari alasan bagaimana bisa
bertahan menginap di RSI Siti Khodijah, eh Mas Santoso memberi peluang. Hingga
malam ke delapan, saya sukses menginap gratis di RSI Siti Khodijah.
Namun, malam kesembilan, masalah yang sama muncul lagi. Istri
Mas Santoso sudah boleh pulang. Padahal, saya masih butuh menginap semalam
lagi. Malam terakhir.
Kali ini, saya tidak mungkin berpura-pura lagi. Segera saya
temui satpam rumah sakit yang berjaga. Kebetulan, satpam yang menegur saya pada
malam pertama yang bertugas.
‘’Pak Satpam, sebenarnya saya ini berpura-pura menunggu pasien.
Saya sebenarnya sedang tes di Jawa Pos. Karena uang saya terbatas, terpaksa
saya mencari tumpangan menginap,’’ jelas saya.
Saya sudah membayangkan, satpam itu akan marah karena
pengakuan jujur saya. Ternyata satpam itu berbaik hati. ‘’Kalau sampeyan ngomong dari awal, sampeyan
bisa menginap di mushola. Syaratnya sudah harus bangun sebelum adzan subuh,’’
jawab satpam tersebut.
‘’Jadi malam ini saya boleh menginap di mushola?’’ tanya
saya.
‘’Boleh. Silakan. Di teras mushola itu ada karpet khusus
untuk tidur satpam. Sampeyan tidur saja di situ,’’ jelas satpam.
Plong! Selamatlah saya malam itu. Tidur di atas karpet yang
hangat.
Sebelum adzan subuh berkumandang, saya sudah bangun. Di luar
rumah sakit sudah ada agen koran yang sedang membagi-bagi jatah kepada para
loper.
Saya beli satu eksemplar. Saya buka halaman paling belakang,
tempat pengumuman hasil seleksi diiklankan setiap hari.
Alhamdulillah... Nama Joko Intarto tertera pada urutan nomor
lima dari 11 wartawan dengan kualifikasi wartawan berita kota Surabaya.
Setelah subuh, seperti biasa saya pergi ke kantor Jawa Pos.
Tetap berjalan kaki. Apalagi uang di dompet sudah nyaris habis.
Hitungan saya, setelah dipakai makan pagi, uang saya bakal
ludes. Tidak ada lagi uang untuk membeli tiket bus ke Semarang untuk mengambil
sepeda motor.
Sekitar pukul 09.00, saya bertemu Mbak Oemiyati, sekretaris
redaksi Jawa Pos. Saya melaporkan sebagai wartawan baru yang lolos seleksi
tahap akhir dan harus mulai bekerja tiga hari kemudian.
‘’Gaji Anda Rp 200 ribu,’’ kata Mbak Oemi.
‘’Bisa diambil sebulan setelah bekerja,’’ lanjutnya.
‘’Ya Mbak. Cuma bolehkah saya utang Rp 100 ribu?’’ tanya
saya.
‘’Kerja saja belum kok sudah utang?’’ tanya Mbak Oemi
setengah heran.
‘’Begini Mbak, saya kehabisan uang. Saya harus pulang ke
Semarang mengambil sepeda motor untuk bekerja,’’ jawab saya.
‘’Oh begitu. Kamu saya kasih surat saja, nanti kasih ke sopir
Jawa Pos. Anda boleh nunut sampai Semarang bareng truk angkutan koran,’’ kata
Mbak Oemi.
Jadilah malam itu saya naik truk dan tidur di atas tumpukan
koran Jawa Pos yang dikirimkan ke kantor biro Semarang. (bersambung)
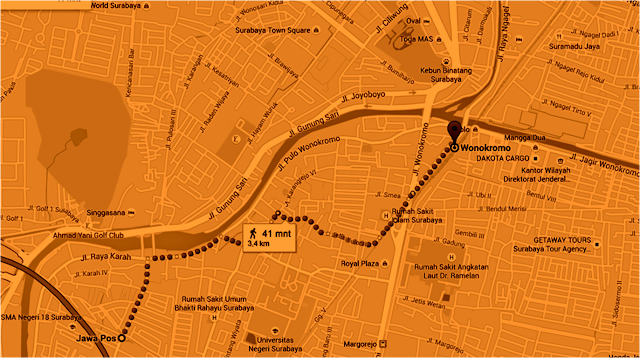



Komentar
Posting Komentar